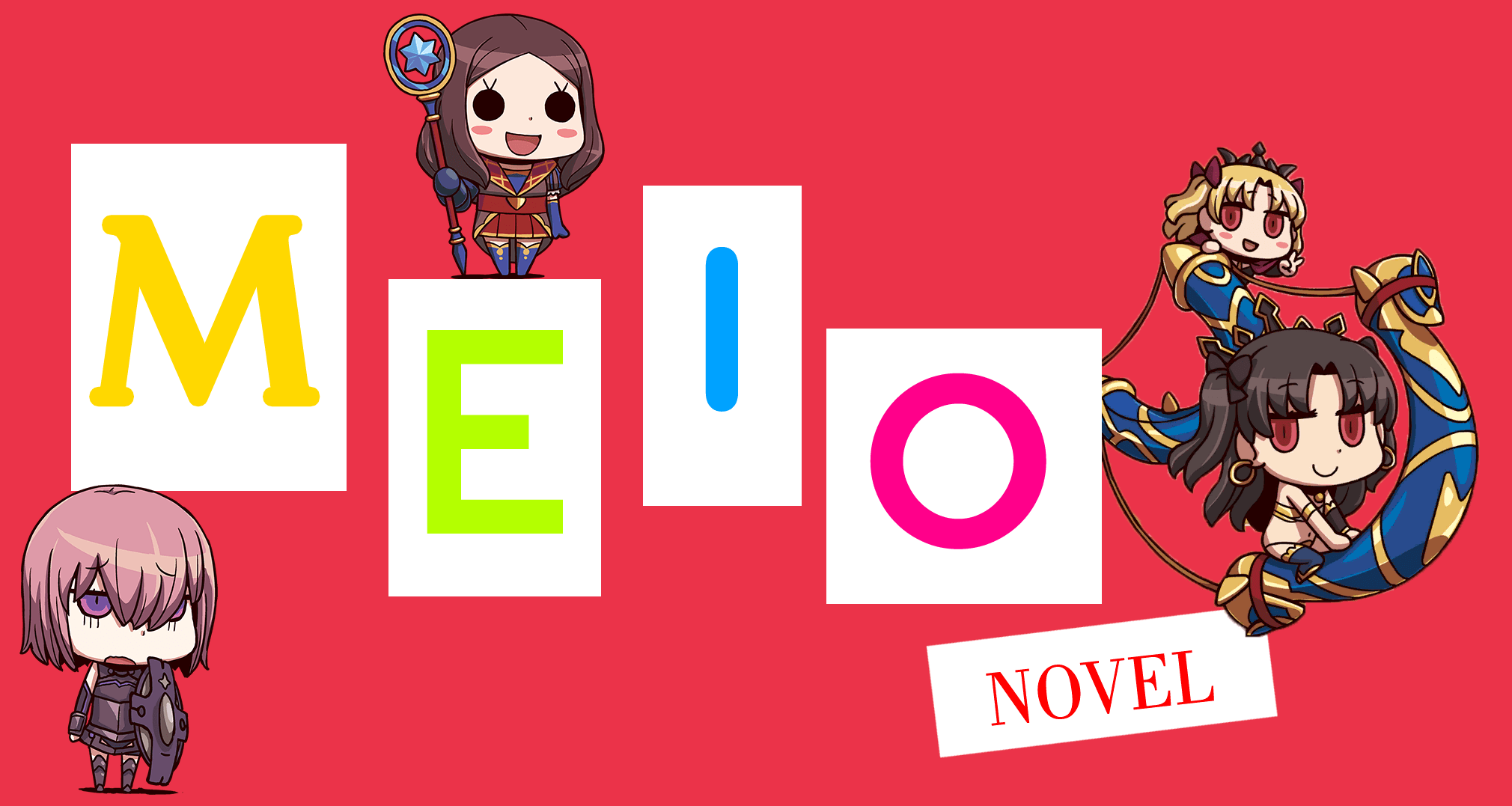- Home
- Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken LN
- Volume 6 Chapter 9

Itu adalah hari terakhir liburan musim panas.
Kalau saja terjadi di tahun lain, Amane pasti akan beristirahat di rumah, tidak pergi ke mana pun. Apalagi sekarang Ia sudah memiliki Mahiru. Tapi pada hari itu, Amane sedang pergi keluar.
Dia bersiap-siap, berdandan secukupnya agar tidak menyinggung perasaan orang yang ditemuinya, lalu menuju ke tempat yang telah disepakati.
…Saya harap ini tidak memakan waktu terlalu lama.
Dia tidak gugup berbicara dengan seseorang yang tidak dia kenal. Ia khawatir jika percakapan ini berlarut-larut, Mahiru akan semakin cemas.
Mahiru berpura-pura tenang ketika Ia memberitahunya bahwa Ia akan bertemu ayahnya, tapi Ia tahu Mahiru tidak mungkin merasa nyaman dengan hal itu. Jelas sekali kalau dia khawatir dengan apa yang mungkin dikatakan ayahnya—dan apa yang akan dipikirkan Amane tentangnya.
Amane tidak ingin meninggalkan Mahiru sendirian dalam keadaan seperti itu lebih lama dari yang seharusnya, jadi Ia bertekad untuk memastikan niat sebenarnya pria itu secepat mungkin.
Terbebani oleh emosi yang besar, Amane berjalan dengan susah payah menuju tempat pertemuan. Kemudian, saat dia mendekati kafe—tidak jauhdari gedung apartemennya—dia melihat orang yang ingin dia temui di sana dan menegakkan tubuh.
Berdiri di hadapan Amane adalah seorang pria berpenampilan lembut, berkulit putih dengan rambut kuning muda dan mata berwarna karamel, seperti yang biasa Ia lihat setiap hari.
Itu adalah pria yang sama yang pernah dia temui sebelumnya—dan dengan siapa dia melakukan percakapan ringan. Mereka belum bertukar nama, tapi Amane sudah mendengarnya dari Mahiru, jadi Ia tahu siapa dirinya.
“Tn. Asahi Shiina?”
Saat Amane menyebut nama pria itu, Ia—Asahi Shiina—berpaling untuk melihat ke arah Amane, dan senyum tipis muncul di wajahnya.
“Senang bertemu denganmu…,” katanya. “Yah, sebenarnya ini bukan pertemuan pertama kita, tapi ini pertama kalinya kita berbincang dimana kita berdua tahu siapa satu sama lain.”
“…Saya rasa begitu. Aku sudah mendengar sedikit tentangmu dari Mahiru.”
Pria itu tidak tampak terguncang saat Amane dengan santai memanggil Mahiru dengan nama depannya, jadi Ia mungkin sudah menyelidiki hubungan mereka.
Sebagai tanggapan, senyuman tipis Asahi menjadi sedikit tegang. Ia memberikan kesan sebagai orang yang tenang, tidak penakut, dan pada pandangan pertama, Ia bukanlah tipe monster yang akan mengabaikan Mahiru saat masih kecil. Meski begitu, penampilan bisa saja menipu, dan ini hanyalah kesan pertama.
“Kalau begitu, kita bisa langsung melakukannya,” kata Asahi. “Bolehkah aku meminta sedikit waktumu?”
“Itulah sebabnya kamu mengajakku ke sini, bukan?” Jawab Amane.
“Memang. Saya sangat bersyukur Anda menerima permintaan saya yang tiba-tiba. Meskipun aku bertanya, aku tidak pernah berharap kamu setuju.”
“Aku bertanya-tanya kenapa kamu berusaha keras untuk menghubungiku… Bukankah kamu seharusnya bertemu dengan Mahiru?”
Amane tidak yakin dengan niat Asahi, dan meskipun begitumenyadari bahwa dia seharusnya bersikap ramah terhadapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan sedikit pun pikirannya kepada pria itu.
Asahi sepertinya mengerti apa yang dimaksud Amane, dan Ia mengerutkan kening dengan tidak nyaman. “Kalau kamu mengatakannya seperti itu, kamu benar, tapi…aku yakin dia tidak ingin melihatku,” katanya.
Dengan senyum masam, Asahi tampak dipenuhi penyesalan.
Amane marah padanya atas nama Mahiru. Dia tidak berpikir dia akan bisa memaafkannya. Tapi pria di hadapannya tidak tampak seperti monster yang tidak berperasaan. Jika ya, tentu saja dia tidak akan melakukan apa pun, betapapun tidak langsungnya, secara diam-diam melakukan kontak dengan putrinya.
Keraguan Amane semakin bertambah.
Kenapa Ia tidak bertemu langsung dengan Mahiru—dan malah bertele-tele dengan menghubungi seseorang yang dekat dengannya?
Amane masih tidak tahu apa yang Ia pikirkan atau apa yang Ia inginkan dari hal ini.
Asahi pasti menyadari tatapan bingung di mata Amane. Dia menggaruk pipinya dan tersenyum canggung.
“Kamu juga pasti punya banyak hal yang ingin kamu tanyakan padaku, kan? Kita tidak bisa ngobrol panjang lebar di sini, jadi bagaimana kalau kita pergi ke kafe?”
Memang benar, tidak mungkin mereka bisa melakukan percakapan mendalam sambil berdiri di jalan, jadi Amane setuju dan berjalan ke kafe bersamanya.
“Pesan apapun yang kamu suka. Lagipula, akulah yang memanggilmu ke sini pada hari terakhir liburan musim panasmu yang berharga.”
Kafe, yang sering dikunjungi Amane, memiliki ruangan pribadi yang bisa dipesan melalui reservasi. Asahi pasti sudah memesannya terlebih dahulu karena mereka ditunjukkan ke salah satu dari mereka.
Begitu mereka duduk berhadapan, Asahi menawarinya menu, senyum lembut di wajahnya.
Amane mengatakan Ia akan menerima tawarannya dan memberitahunya bahwa Ia akan mendapatkan sepiring kue spesial harian yang disertakan dengan kopi, seperti yang tercantum di menu. Asahi memesan hal yang sama.
Kemudian Asahi duduk dengan ekspresi lembut yang sama di wajahnya dan tidak membuka mulut sampai pesanan mereka diantar.
Amane mengira Ia mungkin diam karena Ia tidak ingin para staf mendengar percakapan mereka. Namun bagi Amane, yang duduk di hadapan seorang pria yang usianya tidak jauh berbeda dengan ayahnya sendiri, situasinya terasa sangat canggung.
Untuk mengalihkan perhatiannya, dia secara mental mengatur hal-hal yang ingin dia tanyakan hari itu, dan sekitar ketiga kalinya dia mengulangi latihan, perintah akhirnya diberikan kepada mereka.
Setelah memastikan pelayannya sudah pergi, Amane angkat bicara.
“Jadi, ada urusan apa denganku?”
Agak tidak sopan menanyakannya secara tiba-tiba, tapi Asahi hanya tersenyum. Tampaknya dia tidak tersinggung.
“Tentu saja. Sepertinya Anda berkencan dengan putri saya, jadi saya ingin bertanya bagaimana kabarnya… Saya rasa itulah cara terbaik untuk menjelaskannya.”
“…Dia baik-baik saja.”
“Aku tahu kamu mewaspadaiku.”
“Apa menurutmu aku tidak akan seperti itu?”
“Tentu saja tidak; akan aneh jika kamu tidak melakukannya.”
Asahi mengangguk, dan Amane mengerucutkan bibirnya. Dia tidak yakin bagaimana harus merespons.
Jika, misalnya, Asahi bersikap kejam terhadap putrinya seperti ibu Mahiru, Amane bisa saja bersikap tegas dan menghadapi situasi ini dengan berbagai cara.
Tapi perasaan yang Amane dapatkan dari Asahi adalah Ia mengkhawatirkan putrinya. Dia sepertinya bukan tipe orang yang akan menelantarkan anaknya. Hanya berdasarkan satu percakapan ini, dia tampak seperti ayah yang baik.
Itu membuat Amane bertanya-tanya kenapa Ia meninggalkan Mahiru.
Mungkin saja Ia memasang wajah ramah—dan Ia mungkin akan berubah saat Ia mendapatkan kesempatan untuk melakukan kontak dengan Mahiru. Tapi intuisi Amane mengatakan kepadanya bahwa bukan itu masalahnya.
“Saya sendiri ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Kenapa saat ini kamu berusaha keras untuk mencoba lebih dekat dengan Mahiru?”
Itu karena Amane telah melihat betapa Mahiru telah disakiti oleh ayahnya sehingga Ia merasa sangat tidak menyenangkan jika pria itu muncul sekarang, selamanya.
Tak peduli berapa tahun telah berlalu, duri luka yang menusuk hati putrinya tak kunjung keluar, dan ia menderita selama ini.
Baru-baru ini, duri itu baru saja mulai lepas dan lukanya mulai sembuh, jadi pemikiran untuk membiarkannya terluka lagi tidak dapat ditoleransi.
Amane, yang berniat menghabiskan hidupnya di sampingnya, tidak ingin Mahiru menderita luka yang tidak perlu. Dia menolak membiarkannya mengalami rasa sakit yang tidak perlu.
Selama Ia dan Mahiru bergerak maju bersama, saling mendukung, jika memungkinkan untuk mencegah cedera seperti itu, Ia akan melakukannya, dan jika Ia dapat melindungi Mahiru dari bahaya, Ia juga bermaksud melakukan hal itu.
“…Kamu benar-benar merawat gadis itu dengan baik, bukan?”
Asahi sepertinya terkesan. Ia menatap Amane dengan ekspresi senang—dan tanpa membalas rasa permusuhan yang diarahkan padanya.
“Saya tidak berpikir untuk mencoba membawanya kembali bersama saya atau apa pun. Anda tampaknya khawatir, tetapi saya tidak bermaksud melakukan apa pun yang mengancam nyawanya di sini.”
“…Benar-benar?”
“Tentu saja… saya tidak punya hak untuk mengganggu kehidupannya sekarang. Aku bahkan tidak mempertimbangkannya.”
“Jadi kenapa kamu benar-benar mencoba melakukan kontak dengan Mahiru?”
“…Jika kamu mengatakannya seperti itu, sulit untuk dijelaskan. Saya hanya datang untuk melihat wajahnya.”
“Meskipun kamulah yang meninggalkannya?”
Amane sadar sepenuhnya bahwa ini bukanlah sesuatu yang harus dikatakan oleh orang asing, orang luar seperti dirinya.
Namun perlakuan yang Mahiru derita di tangan orangtuanya tidak bisa dimaafkan.
Karena mereka, Mahiru terus-menerus terluka, dan untuk menyembunyikan rasa sakitnya, dia mengenakan topeng seorang gadis yang menawan dan sempurna. Dia telah menjangkau mereka, memohon untuk dicintai.
Jadi mengapa seseorang yang tidak pernah sekalipun menghadiahi Mahiru atas usahanya untuk menghubunginya kini mengalihkan pandangannya ke arahnya?
Jika Ia mengulurkan tangan padanya secara tiba-tiba, Amane ingin menepis tangannya. Meski beberapa orang mungkin mengatakan Amane bertindak karena kebencian yang egois, Ia bermaksud menjauhkan Mahiru dari apa pun yang mungkin menyebabkan Mahiru menangis atau kesakitan.
Yang mengejutkan, Asahi menunjukkan rasa hormat pada Amane. Ia tidak terlihat marah, dan Ia hanya menatap tatapan Amane dengan ekspresi tenang.
“Kamu suka langsung ke pokok permasalahan, bukan?”
Meski pria yang lebih tua itu marah padanya, satu-satunya hal yang Ia tunjukkan pada Amane adalah ekspresi tenang itu, yang menyulut api kemarahan Amane.
Agar tidak meledak, dia mengepalkan tangannya erat-erat di bawah meja, menyalurkan impulsnya ke dalam tinjunya.
“Kamu benar, tentu saja. Saat ini, saya tidak punya hak untuk bertindak seperti orang tua. Patut dipertanyakan apakah dia masih mempertimbangkankuuntuk menjadi ayahnya. Aku yakin dia mungkin menganggapku lebih seperti orang asing yang memiliki hubungan darah dengannya.”
“…Jika kamu menyadarinya, kamu juga harus memahami apa yang kamu lakukan padanya.”
“Saya tidak akan pernah bisa lepas dari perbuatan saya, selama saya hidup… Sayo dan saya gagal memenuhi peran kami sebagai orang tuanya. Saya yakin orang-orang akan menyebut cara kami memperlakukannya sebagai pengabaian. Wajar jika dia menyalahkan kita.”
Asahi dengan tenang memandang secara objektif kelakuan buruk dirinya dan istrinya. Amane menggigit bibir bawahnya.
Mengapa tidak lebih awal?
Mengapa dia tidak bisa merenungkan tindakannya sebelumnya?
Jika Ia mampu melakukan itu, Mahiru tidak akan terluka seperti dirinya. Sekalipun dia tidak bisa mendapatkan cinta apa pun dari ibunya, dia mungkin menerimanya dari ayahnya. Dia mungkin bahagia.
Mengapa dia bertobat sekarang?
Amane tidak tahu ke mana Ia harus mengarahkan amarahnya.
Dia mungkin tidak berhak untuk marah. Kemarahannya mungkin tidak masuk akal.
Meski begitu, hal itu meluap-luap dalam dirinya.
Amane mau tidak mau bertanya-tanya mengapa pria ini tidak mengulurkan tangan pada putrinya lebih awal.
Jika mereka berada di luar, dia mungkin akan meninggikan suaranya dan mencengkeram kerah baju Asahi. Tapi Amane tetap tenang, mengetahui bahwa Ia tidak boleh membuat keributan di kafe dan mengambil risiko membiarkan orang asing tahu bahwa mereka sedang membicarakan Mahiru. Setelah mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi, dia menolak membuat keributan.
Itu merupakan taktik brilian dari pihak Asahi untuk memilih tempat ini.
“Apakah kamu tahu apa yang dia katakan? Mahiru mengatakan jika dia memang seperti ituketidaknyamanannya, dia seharusnya tidak dilahirkan… Anda dan istri Anda mendorongnya untuk mengatakan itu.”
“…Memang.”
Amane berbicara dengan suara datar dan sangat serius saat Ia entah bagaimana berhasil menahan gemetar. Sementara itu, mata Asahi tampak memahami dan menerima sepenuhnya semua yang dia katakan.
Reaksi pria itu hanya membuat Amane semakin kesal.
“Jika kamu akan mengabaikan Mahiru dan kemudian merasa tidak enak karenanya, kamu seharusnya berkomitmen padanya sejak awal. Jika kamu melakukan itu, dia tidak akan terluka parah.”
“Tidak ada yang bisa saya katakan mengenai hal itu… Tentu saja, saya sepenuhnya sadar bahwa saya telah melakukan hal terburuk yang dapat dilakukan orang tua.”
“… Kalau begitu, sungguh, kenapa sekarang…? Mengapa kamu mencoba menemuinya sekarang? Jika bertemu denganmu hanya akan menyakiti Mahiru, aku tidak ingin kamu melihatnya. Saya tahu saya hanya orang luar, tetapi jika hal itu hanya akan membuatnya kesal, saya tidak ingin hal itu terjadi.”
Tidak mungkin dia bisa mengganggu pertemuan antara ayah dan anak perempuannya. Tapi Mahiru tidak ingin melihat pria itu, jadi Amane mendapati dirinya berbicara dengan tegas.
Meski pria itu mencelanya, Amane tidak berniat menyerah.
Asahi menerima tatapan tajam Amane sambil tersenyum pahit dan meminta maaf.
“Kenapa aku ingin bertemu dengannya? …Saya kira saya tidak yakin.”
“Apakah kamu menghindari pertanyaan itu?”
“Saya tidak bermaksud demikian. Hanya saja—sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, Anda tahu? …Saya kira…Saya pikir saya akan mencoba menemuinya selagi saya masih bisa.”
“Apakah itu berarti kamu tidak akan bisa melihatnya lagi di masa depan? Atau mungkin kamu tidak berniat melakukannya?”
“Itu benar.”
Rasa pahit muncul di mulut Amane saat konfirmasinya.
“…Kamu pria yang egois.”
“Kamu benar, aku egois. Dan saya tidak bermaksud untuk berubah, saya juga tidak berpikir saya bisa berubah pada saat ini. Tapi aku juga tidak ingin membuat putriku merasa tidak bahagia lagi. Jadi mungkin yang terbaik adalah dia membenciku.”
“Aku tidak memahami maksudmu.”
“Kamu akan melakukannya, cepat atau lambat.”
Dari sorot mata Asahi yang penuh arti, Amane tahu kalau Ia tidak berniat mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini, jadi Ia menyerah untuk mendesaknya.
“Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan padaku?” Asahi bertanya.
“…Tidak, aku baik-baik saja.”
“Begitu… Kalau begitu, bolehkah aku menanyakan satu hal lagi?”
Amane tidak tahu apa pertanyaan Asahi, jadi Ia sedikit waspada.
“Teruskan.”
“…Gadis itu, apakah dia bahagia sekarang?”
Asahi menanyakan pertanyaannya dengan ekspresi lembut yang sama dan tidak berubah. Nada suaranya dan sorot matanya memohon kebahagiaan putrinya.
Amane mengepalkan tangannya, lalu menghela nafas pelan.
“…Tidak ada cara untuk mengetahuinya tanpa menanyakannya sendiri. Tapi aku berusaha membuatnya bahagia. Saya yakin saya bisa dan saya akan melakukan yang terbaik.”
Kata-katanya penuh aspirasi, kebanggaan, dan tekad.
Dia tidak pernah bermaksud berpisah dengan gadis lembut dan mungil yang haus akan cinta.
Dia ingin membuatnya selalu tersenyum—dan menjadi orang yang membuatnya bahagia. Dia bertekad untuk melakukan hal itu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, dia tidak berniat untuk goyah dari tujuan itu.
Ketika Amane menyatakan niatnya dengan jelas dengan suara yang tegas dan datar,mata berwarna karamel di seberang meja terbuka lebar, lalu, pada saat berikutnya, melembut dalam kelegaan yang tak salah lagi.
“Jadi begitu. Saya senang mendengarnya.”
Sesuatu dalam senyuman lembut Asahi mengingatkan Amane pada Mahiru.
“…Bukan hakku untuk menanyakan hal ini padamu, tapi tolong jaga dia.”
“Aku akan membuatnya bahagia, baik kamu memintanya atau tidak.”
“Begitu… Terima kasih.”
Meskipun Amane mungkin pantas dimarahi karena nada suaranya dan sikap kasarnya, Asahi tersenyum bahagia padanya.
Melalui perasaan yang rumit, Amane menjawab, dengan suara yang tidak terlalu tajam dibandingkan sebelumnya, “Tidak ada alasan bagimu untuk berterima kasih padaku.”
Saat Amane kembali ke rumah setelah berpisah dengan Asahi, Mahiru diam-diam duduk di sofa.
Biasanya, ketika dia berada di tempatnya, dia datang ke pintu untuk menyambutnya ketika dia sampai di rumah. Namun pada hari itu, dia sepertinya tidak bisa bergerak.
Mahiru menunjukkan ketenangan dengan sedikit ketidaknyamanan. Dia sebenarnya tidak tampak tenang, lebih seperti dia memaksakan dirinya untuk tenang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Amane, tanpa mengatur ekspresinya sama sekali.
“Saya berbicara dengannya,” katanya.
“Apakah kamu?”
Nada suaranya yang sedikit dingin mungkin adalah hasil dari usahanya untuk tetap tenang.
Sebagai tanggapan, Amane memandangnya selembut yang Ia bisa dan diam-diam mengambil tempat duduk di sampingnya.
Begitu Amane sudah duduk di samping Mahiru, dia dengan lembut membungkuk dan meringkuk di hadapan Mahiru. Itu bukan perilaku manisnya yang biasa. Sebaliknya, dia memberi kesan pada Amane bahwa dia bergantung padanya untuk meminta dukungan.
…Dia pasti cemas.
Dia berpura-pura seolah itu bukan masalah besar, tapi ayah yang mengabaikannya telah melakukan kontak setelah sekian lama—dan juga dengan pacarnya.
Mahiru sepertinya tidak menganggap ayahnya adalah karakter yang buruk, tapi dia pasti masih cemas dengan pertemuan mereka.
“Tidak ada hal seperti yang kamu khawatirkan… Dia tenang dan pendiam sepanjang waktu, lebih dari yang kubayangkan.”
“Oh begitu.”
“…Haruskah aku memberitahumu apa yang kita bicarakan?”
“Apapun yang kamu mau. Jika menurutmu yang terbaik adalah memberitahuku, silakan lakukan.”
Bahkan saat Ia mengatakan akan menyerahkannya pada Amane, Mahiru tampak sedikit takut mendengar apa yang Amane katakan. Amane meremas tangannya yang gemetar.
Dia telah memutuskan dia harus terus maju dan memberitahunya.
Dia tidak sepenuhnya memahami apa yang dipikirkan ayahnya ketika dia memilih untuk bertemu, bukan dengan putrinya, tapi dengan pacar putrinya. Tapi Amane merasa setidaknya dia harus memberi tahu Mahiru bahwa ayahnya tidak berniat membuatnya tidak bahagia.
“Aku yakin Asahi tidak berniat melakukan apa pun padamu. Dia memberitahuku bahwa dia tidak berencana menghancurkan hidupmu saat ini.”
“…Saya senang mendengarnya.”
“Lalu aku bertanya kenapa dia ingin bertemu denganmu, tapi dia tidak menceritakan semuanya padaku. Hanya saja dia tidak akan bisa melihatmu lagi, jadi sebelum itu terjadi, dia ingin memeriksamu untuk terakhir kalinya… Itulah inti dari apa yang dia katakan.”
Mendengar kata-kata Amane, Mahiru menggerutu, “Dia belum pernah menemuiku sebelumnya, jadi ini agak terlambat.”
Tapi suaranya sepertinya membawa lebih banyak kepahitan daripada penghinaan.
“…Ini hanya kesanku saja,” Amane melanjutkan dengan ragu-ragu, “tapisaat kita bertemu, Asahi sepertinya dia peduli padamu, Mahiru… Dia bahkan sepertinya ingin kamu bahagia.”
Itulah tepatnya mengapa semuanya begitu membingungkan.
Mengapa Asahi mendoakan kebahagiaan putrinya sekarang? Jika dia menyesal, dia seharusnya tidak mengabaikan anaknya sejak awal. Jika Ia melakukan itu, Mahiru bisa tumbuh tanpa menderita kesepian seperti itu.
Mahiru menghela nafas pelan.
“…Sejujurnya, aku sama sekali tidak mengerti apa yang disebut sebagai orang tuaku.”
Suara Mahiru pelan, tapi sampai ke telinga Amane saat dia melanjutkan. “Mereka pikir mereka telah memenuhi semua tugas mengasuh anak selama mereka memberi saya uang. Mereka hanyalah orang asing yang memiliki hubungan darah denganku. Itulah kesan saya terhadap mereka.”
Dengan nada acuh tak acuh, Mahiru memberi tahu Amane bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Ekspresinya lebih kaku dari biasanya dan sepertinya kurang vitalitas.
“Mereka tidak pernah melihat ke arah saya. Tidak peduli betapa baiknya aku sebagai seorang anak, mereka tidak pernah melihatku. Bahkan saat aku mengulurkan tangan, mereka tidak pernah meraih tanganku… Jadi wajar saja kalau aku berhenti mengulurkan tangan. Dan saya berhenti mengharapkan apa pun dari mereka.”
Amane tahu kalau Mahiru sudah berhenti mengharapkan apa pun dari orangtuanya justru karena mereka selalu mengabaikannya sebelumnya.
Dan dia tidak berpikir bahwa keputusannya salah. Meski masih anak-anak, Mahiru merasa orang tuanya tidak menyayanginya, dan dia tidak bisa mengharapkan apa pun dari mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia telah berhenti berharap. Itu adalah caranya melindungi dirinya sendiri.
“…Saya selalu tahu bahwa ayah saya mampu dalam pekerjaannya dan dia memiliki kepribadian yang baik. Meski begitu, itu tidak mengubah fakta bahwa dia tidak pernah melihat ke arahku, jadi aku tidak yakin bagaimana aku harus memandangnya. Saat ini, saya tidak tahu bagaimana saya harus bereaksi terhadap perhatiannya.”
“Mm.”
“…Benarkah, kenapa sekarang?”
“Mm.”
“Jika dia datang kepadaku lebih awal, aku—”
Kalimat Mahiru terhenti.
Sebaliknya, Amane mendengar embusan napas yang gemetar saat Ia dengan cepat menutup mulutnya.
Bibirnya yang tertutup rapat bergetar hebat, mungkin karena dia mengatupkannya begitu keras, dan dia sering berkedip. Matanya berair seperti hendak menangis, tetapi tidak ada air mata yang tumpah. Dia hanya tampak seperti sedang mencoba untuk diam-diam mengatasi badai yang mengamuk di dalam dirinya.
Sosok fananya tampak seperti akan larut dan menghilang. Amane memeluk Mahiru dan mendekatkan wajah Mahiru ke dadanya.
Seperti yang dia lakukan sebelumnya ketika dia bertemu ibunya, dia menutupinya dengan selimut.
Meski tidak banyak yang disembunyikan kali ini, Amane membungkusnya seluruhnya dan memeluknya erat.
Tubuh halusnya gemetar dalam pelukannya, tetapi dia tidak mendengar isak tangis apa pun.
Tetap saja, dia sepertinya belum siap mengangkat kepalanya. Dia menyerahkan dirinya pada Amane begitu saja dan membenamkan wajahnya ke dadanya.
Saat dia mendongak lagi, area di sekitar matanya tidak merah. Mungkin dia sudah sedikit tenang saat Amane menggendongnya. Matanya sendiri sedikit bimbang, tapi dia tidak terlihat tertekan.
“…Mahiru, apa yang ingin kamu lakukan?”
Amane menunggu sampai Ia sudah tenang untuk menanyakan pertanyaan itu.
Mahiru mengarahkan pandangannya ke bawah. “…Aku tidak tahu,” jawabnya. “Aku hanya—aku menyukai keadaan yang ada sekarang. Meskipun dia akhirnya muncul, aku tidak bisa mengakui pria itu sebagai orang tuanya.”
“Kena kau.”

“…Aku ingin tahu apakah itu salah jika aku mengatakannya, sebagai putrinya?”
“Jawabannya bergantung pada sudut pandangmu, jadi aku tidak bisa memastikannya. Tapi menurutku bukan hal yang aneh jika kamu berpikiran seperti itu, dan aku tidak akan menyangkal hakmu untuk melakukan hal itu. Kalau itu yang kamu rasakan, menurutku tidak apa-apa. Saya menerima pandangan dan pilihan Anda.”
“…Oke.”
Apakah dia salah atau tidak, bukan Amane yang bisa menentukannya.
Secara pribadi, Amane tidak menganggap aneh jika Mahiru tidak lagi mengakui orang tuanya sebagai orang tuanya. Mereka tidak pernah melakukan apa pun sebagai orang tua dan tidak pernah menerima kasih sayangnya, jadi mustahil baginya untuk memandang mereka seperti itu.
“Aku akan selalu ada untukmu, apapun pilihanmu. Saya masih orang luar, jadi saya tidak bisa terlalu terlibat dalam urusan keluarga Anda. Tapi saya menghargai pendapat Anda, dan saya akan mendukung Anda apa pun yang terjadi.”
“…Tentu.”
“Aku akan selalu berada di sisimu. Jika kamu merasa cemas, kamu bisa bersandar padaku.”
Amane sudah mengambil keputusan tentang hal itu.
Ia tidak berniat melepaskan Mahiru. Dia akan menjalani sisa hidupnya berpelukan dekat dengannya.
Dulu, dia pernah mendengar dari teman orang tuanya bahwa orang-orang di keluarga Fujimiya sangat penyayang. Dia tahu dia tidak terkecuali.
Amane tersenyum kecil.
Ia yakin Ia tidak akan pernah kehilangan perasaannya terhadap Mahiru.
Itu bukanlah sebuah prediksi, itu adalah sebuah keyakinan.
Dia selalu mempunyai kecenderungan untuk menyukai satu hal dan terus melakukannya, dan hal itu tidak akan berubah sekarang karena objek yang dia sukai adalah seseorang.
Pacar kesayangannya mengerutkan wajahnya mendengar kata-kata Amane,lalu dia memeluknya, seolah mengatakan dia tidak akan membiarkannya pergi.
“…Kamu benar-benar akan tetap berada di sisiku?” dia bertanya.
“Tentu saja.”
“…Jadi jika aku bilang aku tidak ingin pulang atau sendirian… Jika aku mengatakan itu, maukah kamu menerimanya dan membiarkanku tinggal, Amane?” katanya dengan berbisik muram.
Amane menjawab tanpa ragu, “Apa kamu perlu bertanya?
“Jika itu yang kamu inginkan,” lanjutnya, “Aku akan berada di sisimu selamanya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu… Apakah kamu ingin mencoba menginap di sini, untuk mengujinya?”
Ia menanyakan pertanyaan itu dengan nada yang sengaja menggoda, dan Mahiru, yang sepertinya memahami arti dibalik kata-katanya, langsung berubah dari ekspresi seperti dia akan menangis menjadi merah padam.
Amane tahu persis apa yang Ia katakan, jadi Ia juga merasa malu, tapi ketika Ia melihat bagaimana mata Mahiru melirik ke sekeliling dan bagaimana Mahiru membeku karena malu, Ia merasa lebih bisa mengendalikan diri.
“…Kamu tidak perlu khawatir; kamu tidak akan pernah sendirian lagi.”
Dia membisikkan kata-kata itu dengan lembut, berusaha menenangkan debaran jantungnya. Mata Mahiru berkaca-kaca karena alasan yang berbeda dari sebelumnya, dan dia mengangguk.